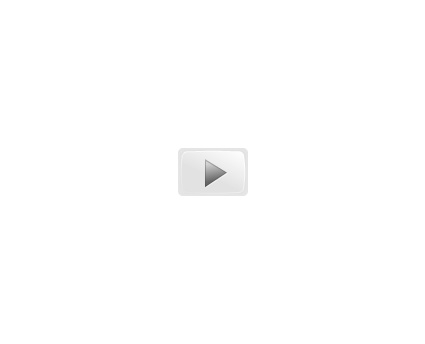“Pesantren Tinggi Imam al-Ghazali Solo”
Hadirnya MAIG akan memberikan
kontribusi yang berarti dalam mencetak guru-guru yang unggul, yang
bergairah dalam mengajar dan mencari ilmu
ILUSTRASI
HARI Sabtu (15/8/2015) ini boleh jadi merupakan salah satu hari bersejarah bagi kaum Muslim di Solo. Hari itu dimulai pembukaan Pesantren Tinggi (Ma’had ‘Aly) Imam al-Ghazali (MAIG). Saya berkesempatan memberikan kuliah perdana dengan tema “Menemukan Jati Diri Pendidikan Islam”. Tema itu sesuai dengan tujuan didirikannya MAIG, yakni untuk mencetak guru-guru unggulan.
MAIG digagas oleh para alumni Program Kaderisasi Ulama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang telah menyelesaikan program Magister Pemikiran Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mereka juga yang bertanggung jawab mengelola dan mengajar di MAIG. Bertindak sebagai mudir al-ma’had adalah Ust. Isa Anshary (Kandidat Doktor Pendidikan Islam di Universtas Ibn Khaldun Bogor). Secara kelembagaan, program ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Peradaban Islam (PSPI) Solo dan Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS) Jakarta.
Dalam UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Ma’had Aly disebut sebagai salah satu bentuk Pendidikan Tinggi. Hanya, hingga kini, belum ada Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang secara teknis menjabarkan bentuk dan kedudukan Ma’had Alu dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Kita berharap, pemerintah memahami bentuk dan system pendidikan Islam, sehingga menempatkan Ma’had Aly setara dengan jenjang pendidikan tinggi di Indonesia.
Sebagai satu lembaga pendidikan berbentuk pesantren, Ma’had Aly memiliki ciri khas: penguasaan ilmu yang mendalam dan keteladanan dalam akhlak mulia. Santri Ma’had Aly dididik langsung oleh mudir al-ma’had (Sang Kiai) dan para guru lainnya, dengan ilmu dan keteladanan. Dengan program pendidikan yang berlangsug selama 24 jam, maka para santri dimungkinkan menyelesaikan pelajarannya dengan lebih cepat, bagi yang mampu. Bisa jadi, untuk menjadi seorang pakar ilmu hadits, seorang santri yang cerdas bisa menyelesaikan dalam waktu 1 tahun saja. Itu setara dengan pendidikan S-1 yang jumlah SKS-nya sekitar 150 SKS.
Di pesantren, seorang Kiai yang memnguasai berbagai bidang ilmu, bisa mengajar beberapa santrinya dengan intensif. Jiwa kesungguhan dan keikhlasan dalam mengajar biasanya melekat dalam diri Sang Kiai. Jika Sang Kiai seorang pakar ilmu sejarah yang shaleh, maka ia harus mendidik para santrinya dengan seluruh ilmu yang dimilikinya. Setelah ilmunya tuntas, santri-santrinya dapat diarahkan untuk berguru kepada ulama lain, sehingga santri-santri itu berpeluang menjadi lebih baik kualitas keilmuannya dibandingkan dengan Sang Kiai.
Sistem pendidikan seperti itulah yang sejak masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassallam telah diterapkan, sampai sekarang, di berbagai lembaga pendidikan Islam. Sistem itu tegak di atas landasan ta’dib, yakni bagaimana mendidikan para pecinta ilmu, agar mereka menjadi manusia-manusia beradab. Sistem pendidikan itu dimulai dari keluarga.
Orangtua adalah yang paling bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya agar menjadi manusia beradab dan berilmu, sebagaimana dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib r.a., bahwa makna QS 66:6 (Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka) adalah: “addibūhum wa ‘allimūhum”. Maknanya, kita diperintahkan, agar keluarga kita tidak masuk neraka, maka didiklah mereka dengan adab dan ilmu. Jadikan mereka manusia-manusia beradab dan berilmu.
Tugas mendidik anak-anak agar menjadi manusia beradab adalah tanggung jawab orangtua. Ketika seorang laki-laki menerima (qabul) dalam akad nikah, sejatinya ia telah membuat perjanjian yang berat (mitsaqan ghalidhan). Sang suami atau sang ayah bukan hanya bertanggung jawab memberi makan anak-anak dan istrinya, tetapi dia juga bertanggung jawab terhadap pendidikan keluarganya. Itu makna hakiki pendidikan Islam. Maka, apa pun profesinya, ayah adalah seorang guru; guru dalam menanamkan adab bagi anak-anaknya.
Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas menggambarkan proses pendidikan itu sebagai: “The purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in man as man and individual self. The aim of education in Islam is therefore to produce a good man… the fundamental element inherent in the Islamic concept of education is the inculcation of adab…”
Jadi, tanggung jawab orangtua, adalah menanamkan nilai-nilai keadilan atau adab dalam diri keluarganya. “Menanamkan” (inculcation) suatu karakter tertentu, bukan sekedar mengajarkan, tetapi memerlukan pemberian keteladanan, pembiasaan, dan penegakan disiplin aturan. Lebih dari pada pendidikan karakter, dalam penanaman adab, diperlukan juga pijakan keimanan dan dukungan doa.
Karena itu, dalam mendidik anak agar menjadi anak yang beradab atau berakhlak mulia – seperti memiliki sifat jujur, pekerja keras, sabar, dan cinta kebersihan, dan sebagainya – harus ditanamkan landasan tauhid, diberikan keteladanan, pembiasaan, penegakan disiplin aturan, dan disertai doa. Itulah kewajiban orangtua. Penanaman adab bisa berhasil dengan baik, meskipun orangtua tidak termasuk kategori ulama atau cendekiawan. Sebab, beradab itu adalah fardhu ain. Siapa pun manusianya, dia harus beradab.
Karena itu, kita sering menjumpai orangtua yang sederhana dan bersahaja bahkan mungkin termasuk kategori miskin, tetapi ia sangat berwibawa dan dihormati di depan anak-anaknya, sebab ia mampu mendidik dan bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Pada saat yang sama, tidak sedikit kita jumpai, orang-orang kaya dan pintar, justru tidak bisa menjadi teladan dan tidak mampu mendidik anak-anaknya sendiri.
Esa sekolah
Kita paham, di masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassallam tidak ada sekolah. Padahal, masa Nabi Shallallahu ‘alaihi Wassallam adalah zaman terbaik (khairul qurun). Nabi Shallallahu ‘alaihi Wassallam dan masyarakat Madinah adalah model ideal. Beliau merupakan suri tauladan (suri tauladan) terbaik sepanjang zaman. Sebelum penjajah masuk ke Indonesia, para ulama telah mengembangkan sistem pendidikan Islam di Nusantara ini, seperti pesantren, madrasah, dan sebagainya.
Penjajah kemudian datang dan memperkenalkan sistem pendidikan sekolah, mulai tingkat sekolah dasar sampai Perguruan Tinggi. Sebagian kalangan Muslim – seperti Mohammad Natsir, dan sebagainya – kemudian mendirikan sekolah-sekolah model Belanda (HIS, MULO, dan AMS), tetapi dengan tambahan pendidikan agama. Kini, setelah penjajah pergi, sistem pendidikan sekolah dianggap sebagai sistem pendidikan utama. Bahkan, tak sedikit yang menyangka, pendidikan itu sama dengan sekolah itu sendiri.
Itulah yang bisa disebut termasuk gejala penyakit sekolahisme, yakni menyamakan antara mencari ilmu dengan bersekolah. Padahal, perintah Nabi Shallallahu ‘alaihi Wassallam sangatlah jelas: mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tentu hadits itu tidak bermakna, bahwa bersekolah itu wajib. Ada juga yang salah kaprah dengan membuat kebijakan “wajib belajar” yang disamakan dengan wajib bersekolah. Bahaya penyakit ini, seorang yang telah selesai sekolah atau kuliah, merasa tidak lagi wajib mencari ilmu. Padahal, mencari ilmu itu wajib sampai mati.
Bahaya lain dari penyakit “sekolahisme” adalah memandang bahwa kewajiban orangtua adalah mencari uang dan mencarikan sekolah untuk anak-anaknya. Ia tidak merasa wajib mendidik atau menanamkan keimanan, adab atau akhlak pada anak-anaknya. Bahkan, untuk mencari ilmu pun ia merasa tidak sempat lagi, karena sibuk dan sudah capek bekerja. Ia merasa cukup dengan mengirim anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang mengajar agama atau mendatangkan guru ngaji untuk anak-anaknya. Ia tidak paham, bahwa kewajiban mendidik anak-anaknya, terletak pada pundaknya.
Seperti disebutkan, penanaman adab atau akhlak pada anak, memerlukan proses yang panjang. Karena itu, orangtua adalah guru terbaik bagi anak-anaknya; dan rumah adalah sekolah terbaik bagi anak-anaknya. Orangtua wajib belajar terus-menerus agar bisa menjadi guru yang baik, utamanya bagi anak-anaknya sendiri. Bukan hanya belajar dan memahami ilmu-ilmu yang diperlukan, kemampuan mendidik juga akan tumbuh bersama praktik pendidikan langsung. Karena itu, sepatutnya, semakin bertambah umurnya, guru-guru akan semakin bijak, karena telah mendapatkan hikmah dari Allah, sehingga bisa menerapkan adab dengan baik. Kebijakan melarang orang menjadi dosen ketika berumur 65 tahun bukanlah kebijakan yang baik, dalam perspektif pendidikan Islam. Sebab, mengajar itu wajib, selama masih mampu mengajar.
Untuk membentuk guru-guru unggulan – baik di rumah maupun di sekolah – itulah tujuan MAIG didirikan. Selama enam bulan para santri – yang merupakan sarjana S-1 – dididik oleh dosen-dosen terbaik agar memahami ilmu-ilmu keislaman, pendidikan, dan juga memiliki kemampuan mendidik. Tidak dapat dipungkiri, berkembang pesatnya begitu banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam di semua jenjang pendidikan, terkadang tidak diikuti dengan penyiapan guru-guru yang baik, yakni guru-guru yang berjiwa mujahid; guru-guru yang bergairah dalam mengajar dan mencari ilmu. Guru bukanlah pekerjaan rutin teknis seperti pekerja pabrik. Tetapi, guru adalah pekerjaan intelektual yang menuntut kecintaan dan kesungguhan. Dengan menghayati peran mulianya sebagai mujahid ilmu itulah maka guru akan terus berkembang keilmuan dan keahliannya dalam mendidik.
Karena itu, seorang intelektual atau ulama yang ilmunya mempuni dan berkemampuan dalam mendidik, perlu mempertibangkan semaksimal mungkin mendidik anak-anaknya sendiri, khususnya dalam menanamkan keimanan dan adab pada anak-anaknya. Jika orangtuanya sendiri bisa mendidik, mengapa harus diserahkan pendidikan anak-anaknya pada guru yang belum jelas kemampuan mendidiknya?
Tidak sedikit orangtua yang menyesal karena kemudian “kehilangan anak”, karena jarang bertemu dan kemudian tidak dapat lagi berkomunikasi dengan anak-anaknya. Ia telah melakukan tindakan yang keliru, menyerahkan anaknya untuk dididik oleh gedung sekolah atau kampus, tanpa memahami proses pendidikan jenis apa yang diterapkan kepada anak-anaknya.
Lebih parah lagi, tidak sedikit orangtua yang hanya tahu bahwa anaknya sudah kuliah di jurusan favorit, di kampus tertentu, tanpa memahami potensi apa yang harusnya dikembangkan pada anak-anaknya. Ia hanya tahu, setelah lulus kuliah, anaknya akan cari kerja, cari jodoh, menikmati hidup, dan kemudian menjadi kebanggan keluarga, dan setelah itu mati. Ia tidak paham, bahwa dengan kecerdasan yang dimiliki anaknya, maka si anak wajib menguasai ilmu-ilmu yang fardhu ain dan fardhu kifayah secara proporsional. Itulah makna adab dan ta’dib (pendidikan).
Karena itu, kunci perbaikan pendidikan adalah pada perbaikan kualitas guru; baik guru di rumah (orangtua) maupun guru di sekolah. Bangkit dan hancurnya bangsa ini bergantung pada ada tidaknya guru-guru yang ikhlas mengabdikan diri untuk ibadah dalam mendidik bangsanya. Untuk itulah, MAIG didirikan. Meskipun saat ini lembaga-lembaga pendidikan guru di tingkat Perguruan Tinggi telah begitu menjamur, tetapi faktanya belum sejalan dengan kualitas pendidikan di Indonesia.
Bahkan, ironisnya, begitu banyak sarjana pendidikan yang tidak memiliki kegairahan dalam mengajar dan mencari ilmu. Itu karena salah paham tentang ilmu dan pendidikan dalam Islam. Jadi, betapa pun kecilnya, kita berharap, hadirnya MAIG akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mencetak guru-guru yang unggul, yang bergairah dalam mengajar dan mencari ilmu. Ke depan, MAIG diharapkan dapat menjadi model untuk pendidikan guru unggulan di Indonesia. Amin.*/Jakarta, 14 Agustus 2015.
Penulis adalah Ketua Program Magister dan Doktor Pendidikan Islam—Universitas Ibn Khaldun Bogor. Catatan Akhir Pekan (CAP) hasil kerjasama Radio Dakta 107 FM dan hidayatullah.com